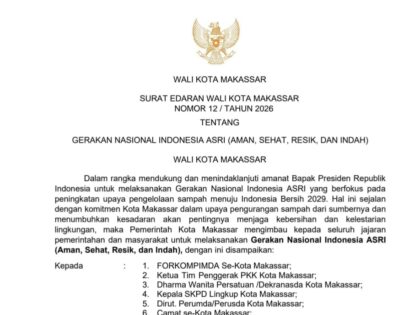INSAN.NEWS || Pangkep 01 Oktober 2025 – Sejak ditetapkan pada 01 Oktober 1945, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan philosophische grondslag—falsafah yang menjadi landasan etika, politik, dan sosial bangsa Indonesia. Ia lahir dari konsensus historis, hasil dialektika antara tradisi lokal, nilai-nilai keagamaan, dan pemikiran modern yang kala itu berhadapan dengan kolonialisme.
Namun, delapan dekade setelah proklamasi kemerdekaan, muncul pertanyaan fundamental: apakah Pancasila masih sungguh menjadi pedoman hidup bangsa, atau hanya tinggal jargon dalam upacara kenegaraan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika bangsa dihadapkan pada tiga gelombang besar: penetrasi ideologi asing, krisis moral, dan tantangan demokrasi.
Ideologi Asing: Globalisasi sebagai Tantangan
Era globalisasi menghadirkan paradoks. Di satu sisi, keterbukaan informasi membawa peluang transfer ilmu, teknologi, dan ekonomi. Di sisi lain, ia juga menjadi pintu masuk bagi ideologi transnasional yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kapitalisme global dengan wajah neoliberalisme menjadikan manusia sekadar instrumen pasar, bukan subjek bermartabat. Di ujung spektrum lain, fundamentalisme keagamaan menolak pluralisme dan mengedepankan dogma tunggal yang mematikan ruang dialog. Dua ekstrem ini—liberalisme tanpa batas dan radikalisme sempit—berpotensi merobek jalinan kebangsaan.
Pertanyaannya: apakah Pancasila masih mampu menjadi “penyaring” ideologi asing, atau ia justru tereduksi menjadi sekadar simbol administratif?
Krisis Moral: Disorientasi Nilai
Krisis moral bangsa tampak telanjang di ruang publik. Korupsi yang merajalela, kekerasan sosial, disinformasi di media digital, hingga lunturnya rasa empati menunjukkan adanya moral vacuum—kekosongan etis yang menegaskan bahwa Pancasila belum sungguh diinternalisasi dalam perilaku.
Padahal, sila kedua dan kelima Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi fakta sosial menunjukkan ketimpangan ekonomi kian menganga, sementara budaya konsumtif semakin menjauhkan manusia dari nilai gotong royong.
Secara filosofis, hal ini mengindikasikan kegagalan dalam menjadikan Pancasila sebagai ethos—roh penggerak kehidupan sehari-hari—dan hanya dipahami sebatas logos—teks normatif di atas kertas.
Demokrasi: Antara Janji dan Realitas
Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi seluas-luasnya. Namun, demokrasi Indonesia kerap jatuh pada paradoks: kebebasan politik tanpa kedewasaan moral. Politik uang, polarisasi identitas, serta lemahnya institusi hukum menandakan bahwa demokrasi belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita Pancasila.
Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat, bukan sekadar mayoritarianisme atau dominasi elite. Demokrasi Pancasila semestinya menempatkan kedaulatan rakyat dalam kerangka kebijaksanaan, bukan transaksionalisme pragmatis.
Dengan kata lain, Pancasila menghendaki demokrasi yang berkarakter etis, bukan sekadar prosedural.
Pancasila sebagai Philosophy of Praxis
Untuk menjawab tantangan di atas, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai doctrine (ajaran mati), melainkan harus menjadi philosophy of praxis (filsafat praksis). Artinya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa direinterpretasi sesuai konteks zaman, tanpa kehilangan jati dirinya.
Ketuhanan bukan sekadar formalitas religius, tetapi kesadaran spiritual yang melahirkan toleransi.
Kemanusiaan bukan retorika, tetapi penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.
Persatuan bukan jargon politik, tetapi energi kolektif untuk mengatasi fragmentasi sosial.
Kerakyatan bukan sekadar pemilu lima tahunan, tetapi praksis deliberasi yang memuliakan akal sehat rakyat.
Keadilan sosial bukan utopia, melainkan komitmen nyata terhadap distribusi kesejahteraan.
Pancasila di Persimpangan
Pancasila hari ini berdiri di persimpangan sejarah. Ia bisa terus menjadi bintang penuntun bangsa, atau meredup menjadi hiasan retorika. Pilihannya ada pada kita: apakah kita bersedia menghidupkan Pancasila dalam praksis nyata, atau membiarkannya terkubur di balik seremoni kenegaraan.
Filsafat mengajarkan bahwa nilai bukanlah sesuatu yang statis, melainkan harus diperjuangkan. Maka, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi “masihkah Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa?”, melainkan “apakah kita, sebagai bangsa, masih sungguh memedomani Pancasila dalam setiap aspek kehidupan?”